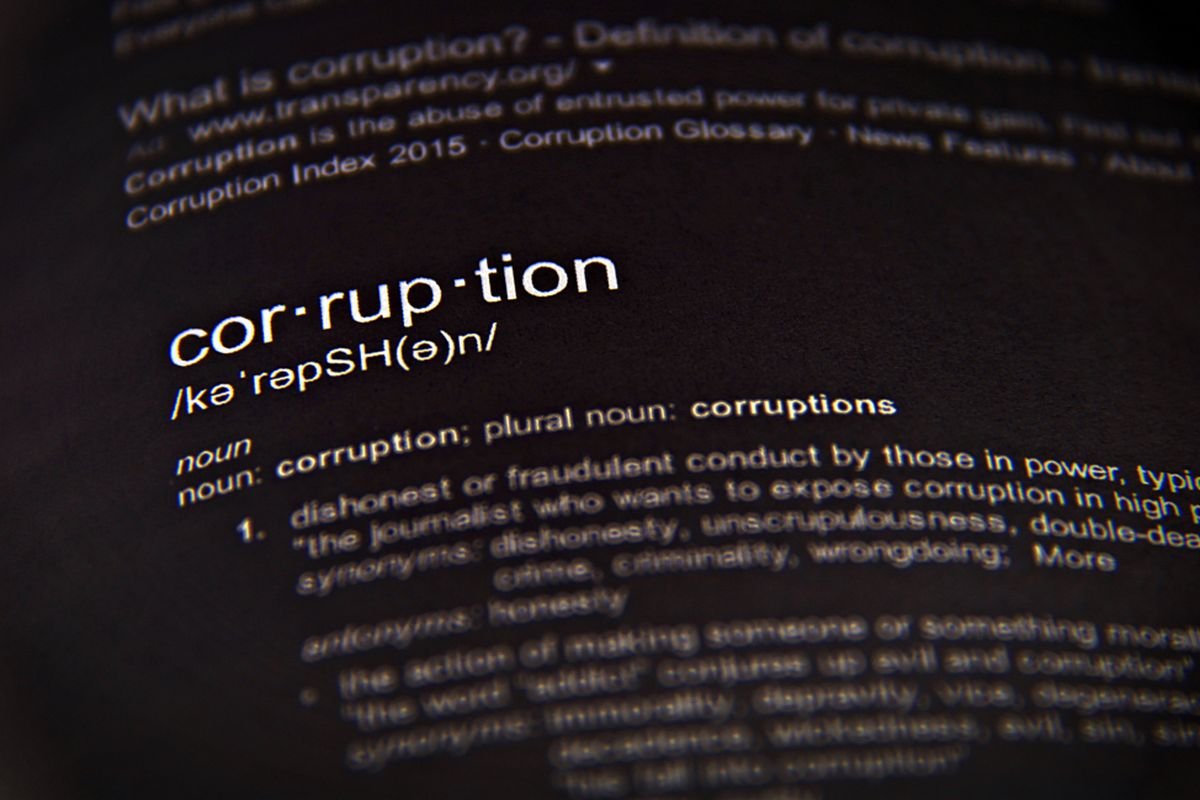
LAHIRNYA UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menimbulkan rasa pesimistis apabila dikaitkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 9G UU tersebut, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.
Dengan adanya ketentuan itu, maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi BUMN, terutama terkait penanganan korupsi.
Sementara pimpinan KPK menegaskan bahwa organ/pengurus/pejabat/pegawai pada BUMN merupakan penyelenggara negara sepanjang memenuhi ruang lingkup Penyelenggara Negara seperti tertuang pada UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Namun, nampaknya gerbang BUMN sudah tertutup untuk pengusutan tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, Pasal 1a ayat (2) UU BUMN mengukuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sebagai pedoman pengelolaan BUMN.
Baca juga:
Meskipun secara kelembagaan telah mengalami transformasi, BUMN masih menjadi episentrum berbagai persoalan dalam praktik pengelolaan keuangan negara.
Kasus-kasus penyimpangan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN menunjukkan adanya kerentanan sistem pengawasan dan lemahnya daya paksa hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan kedudukannya (Kimbal, A., Mawuntu, R., Frederik, W., & Kalalo, F.:2018).
Dalam konteks inilah peran hukum pidana menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat preventif untuk menjaga integritas pengelolaan BUMN.
KPK bersikap
PADA 5 Mei 2025, Ketua KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca-UU BUMN.
Dalam SE internal itu ditegaskan mengenai sikap resmi KPK terhadap sejumlah perubahan aturan di dalam UU BUMN.
SE KPK tersebut menegaskan bahwa kerugian keuangan BUMN, maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), tetap merupakan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 2 dan 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Hal itu tetap berlaku sepanjang kerugian BUMN adalah akibat dari perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan.
Adapun KPK bekerja berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa KPK berwenang menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan.
Adapun yang dimaksud penyelenggara negara dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 itu adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Sehingga direksi dan komisaris BUMN masuk di dalamnya.
Secara lex specialis, Pasal 3X ayat 1 UU BUMN disebutkan bahwa organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.
Kemudian pada Pasal 9G, disebutkan juga anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
Status hukum pejabat dan kekayaan BUMN
Status hukum pejabat BUMN dan kedudukan kekayaannya dalam perspektif hukum pidana menjadi permasalahan penting yang menentukan arah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor strategis negara.
UU BUMN menyajikan konstruksi yuridis baru terkait klasifikasi pejabat BUMN dan karakter kekayaan yang dikelola (Nasution, A., Nasution, B.Saidin,O.,&S.:2020).
Baca juga:
Perubahan tersebut memberikan implikasi signifikan terhadap pembuktian dalam ranah hukum pidana, terutama dalam menjangkau unsur kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat korporasi negara.
Pejabat BUMN dalam kerangka hukum yang berlaku seperti anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas menjalankan fungsi manajerial dan pengawasan terhadap operasional perusahaan negara.
Meskipun memiliki hubungan dengan negara dalam bentuk penyertaan modal dan pemilikan saham, UU BUMN tidak menetapkan secara tegas bahwa pejabat BUMN merupakan bagian dari penyelenggara negara.
Ketentuan normatif mengenai status pejabat BUMN tidak dijabarkan dalam bagian umum maupun bagian substansi undang-undang.
Ketiadaan klasifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap penerapan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama dalam pasal-pasal yang mensyaratkan status pelaku sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik.
Keberadaan unsur jabatan publik atau status sebagai penyelenggara negara dalam delik korupsi memiliki peran krusial dalam membangun konstruksi yuridis atas penyalahgunaan kewenangan.
Ketika pejabat BUMN tidak lagi secara normatif ditempatkan sebagai penyelenggara negara, maka proses pembuktian terhadap unsur jabatan dalam tindak pidana korupsi menjadi terhambat.
Hal ini menciptakan risiko yuridis yang tidak kecil, yakni pelaku yang sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan negara justru luput dari jerat pidana karena ketiadaan dasar hukum formil atas statusnya.
Ketentuan serupa juga berdampak terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam sistem hukum pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu elemen objektif yang harus dibuktikan secara rigid.
Dalam Pasal 25 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa “BUMN merupakan badan hukum privat yang kekayaan dan tanggung jawabnya terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab negara, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya.”
Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa setelah dilakukan penyertaan modal, kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak lagi termasuk kekayaan negara dalam pengertian langsung (Nurhalimah, S: 2022).
Akibatnya, pembuktian atas adanya kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi di BUMN harus memperhitungkan terlebih dahulu apakah kekayaan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara yang dilindungi oleh hukum pidana.
Pada praktik peradilan, penuntut umum harus mampu menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian terhadap kekayaan negara.
Namun, ketika kekayaan tersebut telah dipisahkan secara yuridis dari APBN dan menjadi milik korporasi, proses pembuktian menjadi lebih kompleks.
Perlu dijelaskan secara rinci struktur kepemilikan, aliran dana, serta status kekayaan yang digunakan atau disalahgunakan.
Baca juga:
Jika kekayaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara, maka delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dapat diterapkan.
Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena memerlukan pendekatan pembuktian ekonomi-forensik dan argumentasi hukum yang sangat teknis.
Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik juga menyulitkan penerapan delik suap dan gratifikasi dalam Pasal 5 hingga Pasal 12B Undang-Undang Tipikor.
Pasal-pasal tersebut umumnya mensyaratkan bahwa penerima suap adalah pejabat negara, penyelenggara negara, atau pegawai negeri.
Ketika pejabat BUMN tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori tersebut, maka proses hukum atas pemberian atau penerimaan suap menjadi kehilangan dasar hukum.
Argumen hukum untuk memasukkan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara melalui penafsiran analogi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
Kondisi ini memerlukan pendekatan konseptual baru yang menekankan pada fungsi pejabat BUMN dalam sistem ketatanegaraan.
Meskipun tidak dijelaskan secara formal sebagai penyelenggara negara, pejabat BUMN menjalankan fungsi publik dan mengelola kepentingan negara dalam bidang ekonomi.
Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari manajemen keuangan publik secara substantif.
Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana perlu merujuk pada teori jabatan publik dan tanggung jawab fungsional, bukan sekadar status struktural atau administratif.
Dengan demikian, pejabat BUMN dapat dimasukkan ke dalam cakupan subjek hukum pidana korupsi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatannya berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dan berdampak pada kerugian negara.
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan karakter antara BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan BUMN terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik.
Dalam konteks BUMN non-terbuka, negara tetap memegang kendali penuh atas operasional dan arah kebijakan perusahaan, sehingga fungsi publik tetap melekat secara kuat.
Namun dalam BUMN terbuka, struktur kepemilikan telah bercampur antara negara dan pihak swasta, yang menyebabkan semakin kompleksnya analisis terhadap kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara (Yunus, N., & Nasution, L: 2021).
Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa kekayaan BUMN adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dimiliki oleh BUMN, dan berada dalam penguasaan perusahaan.
Formulasi ini tidak mengaitkan secara langsung kekayaan tersebut dengan keuangan negara, sehingga semakin memperlemah daya jangkau hukum pidana terhadap kerugian yang timbul dari pengelolaan aset BUMN.
Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam membedakan antara kekayaan negara yang melekat pada fungsi publik dan kekayaan yang telah dipisahkan melalui mekanisme korporasi.
Ketiadaan rujukan eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 2025 terhadap keberlakuan Undang-Undang Tipikor memperparah situasi tersebut.
Oleh karena itu, perlu dibangun kerangka hukum interpretatif yang memungkinkan aparat penegak hukum mengaitkan kembali fungsi pejabat BUMN dan kekayaan BUMN dengan kepentingan publik dan keuangan negara.
Pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi BUMN akan selalu membutuhkan pendekatan yang bersifat substansial, tidak hanya formal.
Pembuktian harus menelusuri apakah dana, aset, atau keuntungan yang hilang atau diselewengkan berasal dari sumber daya negara atau berdampak langsung terhadap kepentingan fiskal negara.
Baca juga:
Penggunaan metode audit forensik, pelacakan aliran dana, serta pemetaan struktur kepemilikan aset menjadi penting untuk memperkuat proses pembuktian dalam hukum acara pidana.
Kesimpulan
Rekonstruksi terhadap pemahaman hukum mengenai kedudukan pejabat BUMN dan kekayaan yang dikelola juga perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi teknis dan peraturan pelaksana.
Penetapan status hukum yang lebih eksplisit akan membantu harmonisasi antarlembaga penegak hukum dan menghindari fragmentasi interpretasi hukum (Djalal, D:2021).
Selain itu, penting pula untuk memasukkan klausul dalam peraturan yang memungkinkan pembuktian fungsional atas hubungan antara kekuasaan pejabat BUMN dan potensi penyalahgunaan yang berdampak pada keuangan negara.
Ketika hukum pidana dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap keuangan negara, maka batas antara kekayaan negara langsung dan kekayaan yang dipisahkan harus ditafsirkan secara fungsional dan proporsional.
Negara tidak boleh kehilangan alat hukum untuk menindak perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik, hanya karena adanya konstruksi formal atas entitas korporasi.
Hukum pidana harus tetap menjadi alat efektif untuk menjaga integritas pengelolaan ekonomi negara, termasuk melalui entitas seperti BUMN.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita EDA WEB WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Sumber : Kompas
